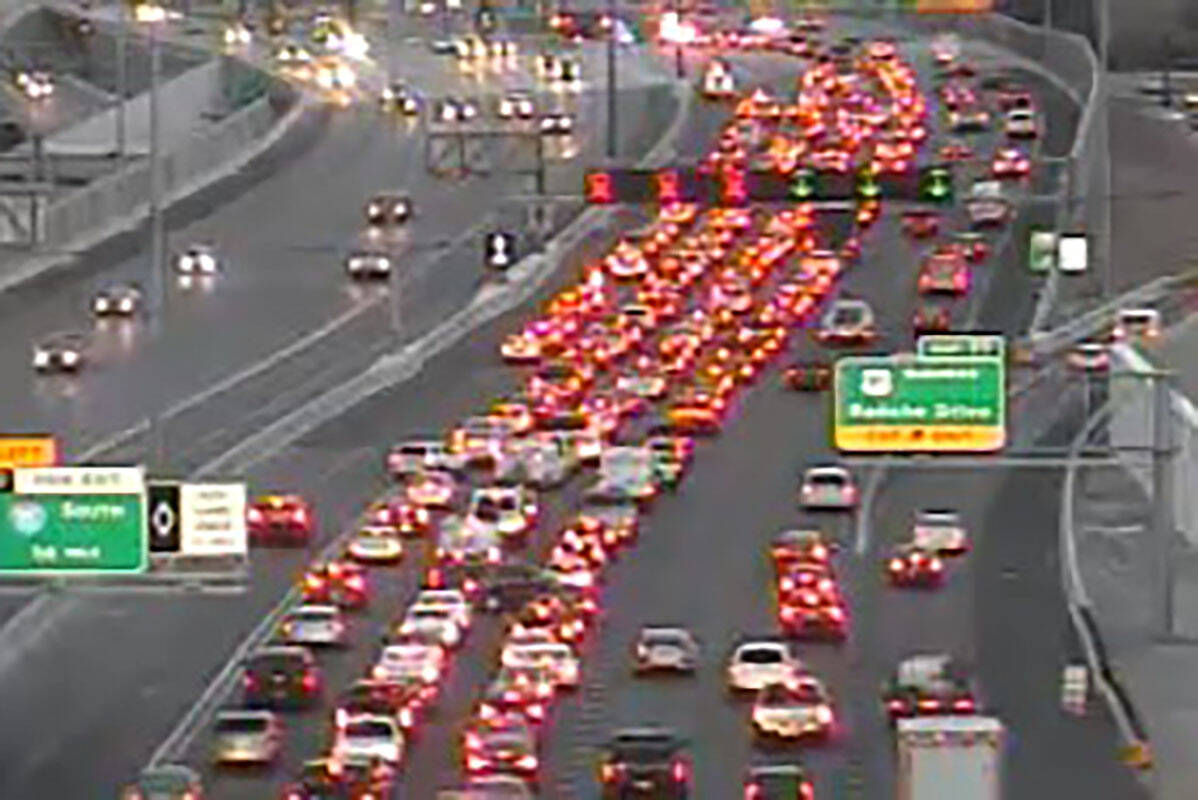KAMPALA, Uganda (AP) – Semakin banyak perempuan yang mulai bercerai di Uganda, sebuah negara konservatif di Afrika Timur di mana perempuan diberdayakan untuk meninggalkan pernikahan yang buruk dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh ibu mereka, kata aktivis hak asasi manusia dan pakar hukum.
Apakah pernikahan Anda sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi? Ini adalah pertanyaan yang diajukan hakim Uganda David Batema kepada perempuan dalam proses perceraian terhadap laki-laki yang seringkali enggan melepaskan istrinya. Apapun yang dikatakan pria, menurut Batema, wanita yang ingin meninggalkan pernikahannya yang gagal sebaiknya tidak didorong untuk berlama-lama.
“Saya biasanya mengubah lapangan saya menjadi ruang kelas belajar,” katanya dalam sebuah wawancara. “Di era kesetaraan gender ini, kami mengatakan bahwa… jika pernikahan tidak bisa menjadi tempat tidur mawar, maka pernikahan tidak boleh menjadi tempat tidur duri. Tujuan utama dari pelajaran ini adalah untuk menunjukkan kepada laki-laki bahwa pernikahan mulai sekarang adalah kemitraan yang setara.”
Aktivis hak-hak perempuan mengatakan posisi Batema adalah tanda perubahan zaman di Uganda, di mana dulunya sangat sulit bagi perempuan untuk bercerai. Proses hukum seperti ini hampir selalu diprakarsai oleh laki-laki, sebuah warisan kepercayaan tradisional yang menekankan kepatuhan perempuan dan undang-undang perceraian yang kini tidak konstitusional.
Pada tahun 2004, pengadilan di Uganda membatalkan undang-undang yang menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi bagi perempuan yang ingin bercerai. Pada saat itu, seorang wanita diminta untuk memberikan bukti yang membuktikan adanya sodomi, desersi atau – mungkin yang paling aneh – sifat kebinatangan yang dilakukan suaminya. Dia, pada gilirannya, hanya perlu membuktikan bahwa wanita tersebut telah melakukan perzinahan.
Meskipun Biro Statistik Uganda tidak mengumpulkan angka perceraian nasional, panitera pengadilan, aktivis dan pengacara mengatakan bahwa mereka kini menangani lebih banyak kasus perceraian dibandingkan satu dekade lalu.
“Jumlahnya terus meningkat,” kata Ismail Jjemba, panitera di Pengadilan Tinggi Uganda, mengacu pada dampak keputusan Mahkamah Konstitusi. “Hampir selalu perempuanlah yang pertama kali mengeluh.”
Perceraian masih mendapat stigma di Uganda, dimana para pejabat gereja mengeluh bahwa perceraian sedang meningkat. Namun iklim hukum yang lebih adil dan peningkatan kesempatan pendidikan bagi perempuan berkontribusi terhadap apa yang disebut oleh seorang aktivis sebagai “normalisasi perceraian” di negara Afrika Timur.
Anggota parlemen Uganda sedang mempertimbangkan undang-undang, yang diperkirakan akan disahkan tahun ini, yang akan memperjelas bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam pernikahan. RUU tersebut bahkan memperkenalkan pelanggaran “perkosaan dalam perkawinan” dan ketentuan pembagian harta perkawinan yang setara jika terjadi perceraian. Presiden Uganda Yoweri Museveni, yang dianggap bersimpati terhadap hak-hak perempuan, mengatakan negaranya membutuhkan undang-undang semacam itu.
“Orang tidak harus mati dalam sebuah pernikahan,” kata Maria Nassali, seorang aktivis perceraian yang mengajar hukum keluarga di Universitas Makerere di Uganda. “Kita perlu menghilangkan stigma yang terkait dengan perceraian. Dia tidak egois ketika dia bercerai. Dia tidak bermoral. Dia hanya ingin menjadi manusia.”
Penelitian menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga perempuan menikah di Uganda pernah mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya. Para aktivis mengatakan praktik tradisional mahar, di mana laki-laki menawarkan hadiah – biasanya ternak – sebagai imbalan bagi pengantin perempuan menghilangkan martabat perempuan dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Batema, sang hakim, mengatakan beberapa pria menginginkan pengembalian mahar mereka di pengadilan ketika proses perceraian dimulai, seringkali memaksanya untuk berdebat dengan mereka yang “berusaha meremehkan peran perempuan” dalam pernikahan.
“Itulah sebabnya dalam karir saya, saya tidak pernah menolak untuk mengabulkan perceraian jika salah satu pasangan menginginkannya,” ujarnya. “Pernikahan seharusnya bersifat sukarela. Kita tidak perlu menunggu untuk mengadili kasus-kasus pembunuhan; kita harus mengabulkan perceraian ketika kita punya kesempatan.”
Pengacara perempuan telah memperhatikan pemikiran seperti itu di kalangan hakim, dan saat ini mereka secara terbuka mendorong perempuan di serikat pekerja yang tidak bahagia untuk mendapatkan bantuan hukum. Asosiasi Pengacara Perempuan Uganda, atau FIDA, menyelenggarakan klinik bantuan hukum bagi perempuan yang membutuhkan di seluruh negeri.
“Saya pikir alasan mengapa perceraian meningkat adalah karena perempuan keluar dari siklus itu, gambaran bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh,” kata Peace Amito dari FIDA. “Di masa lalu, sangat sedikit perempuan yang berpendidikan, sangat sedikit yang merasakan kehidupan di luar desanya. Sekarang kebanyakan dari mereka yang datang ke sini berkata: ‘Saya muak.’ Mereka menyadari bahwa perceraian adalah sebuah pilihan.”