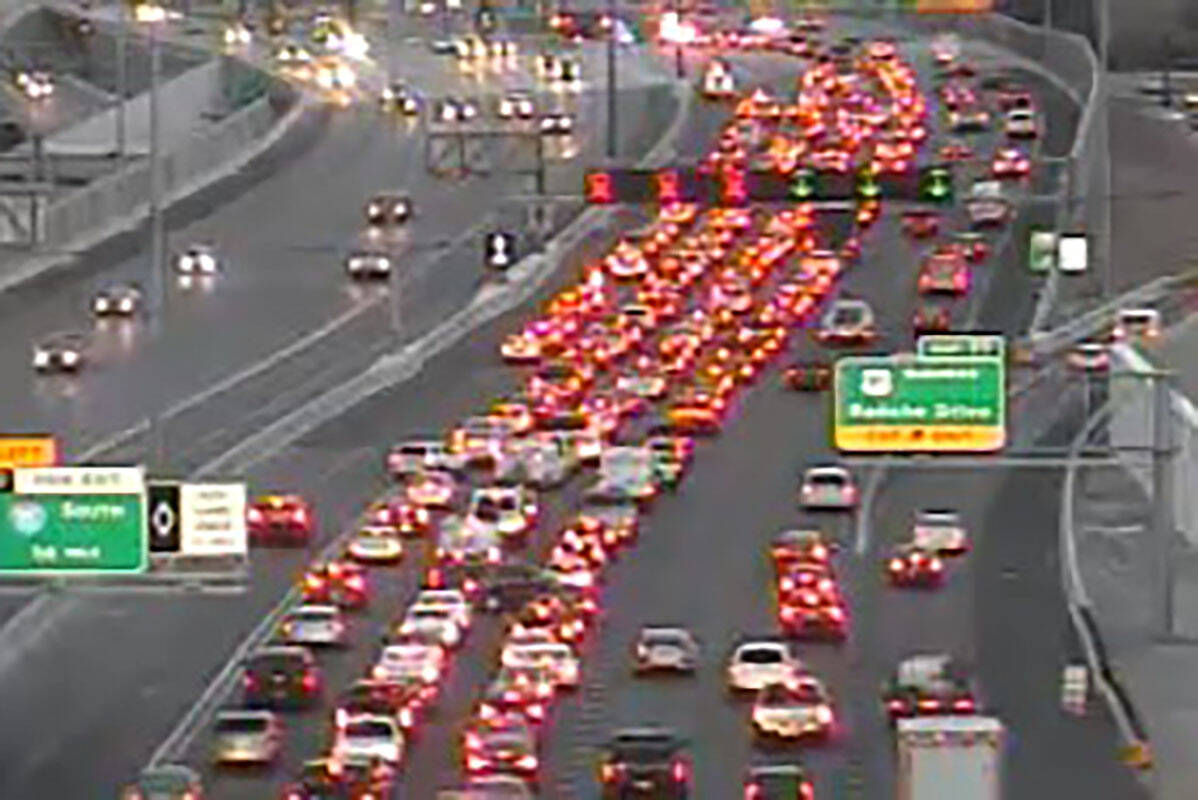NEW YORK (AP) – Berkat kata-kata yang dicetak dan gambar bergerak, Salman Rushdie mendapatkan kembali bagian terburuk dalam hidupnya dan menghidupkan kembali salah satu yang terbaik.
Musim gugur yang lalu, penulis berusia 65 tahun ini menerbitkan memoar terlaris “Joseph Anton” tentang tahun-tahun persembunyiannya setelah penerbitan “The Setan Verses” pada tahun 1988 dan seruan untuk kematiannya oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini dari Iran. Rushdie kini mempromosikan film yang diadaptasi dari novel terobosannya, “Midnight’s Children”, pemenang Booker Prize 1981 dan salah satu karya fiksi paling terkenal pada masanya.
“Menulis ‘Joseph Anton’ adalah katarsis,” jelas Rushdie dalam wawancara baru-baru ini, mengenakan setelan abu-abu dan tanpa dasi, sambil minum kopi di taman atap hotel di tengah kota Manhattan. “Dan ‘Midnight’s Children’ adalah buku di mana saya benar-benar menjadi seorang penulis.”
Sebagian besar dunia baru mengetahui tentang Rushdie setelah “Ayat-Ayat Setan”, yang dikutuk sebagai penghujatan oleh Ayatollah dan yang lainnya dan membuatnya menjadi penulis yang lebih banyak dibicarakan daripada dibaca. Dipaksa hidup dengan nama samaran, Joseph Anton, ia merasa seolah kehilangan kendali atas narasi hidupnya sendiri. Dalam memoarnya, ia mengubah dirinya menjadi semacam karakter sastra, menyebut dirinya sebagai orang ketiga, dan menggunakan narasi untuk mendapatkan kembali miliknya.
“Sekarang waktu itu milik saya,” katanya. “Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi padaku.”
Dalam komunitas sastra, nama Rushdie telah lama menjadi terkenal karena “Midnight’s Children”. Lebih dari 500 halaman, ini adalah narasi berlapis-lapis tentang Saleem Sinai, seorang anak yang lahir pada saat kemerdekaan India dari Inggris, dan petualangannya yang menakutkan, mengasyikkan, dan fantastis yang menghubungkan kisahnya dengan kisah negaranya. Secara luas dianggap sebagai tonggak fiksi neo-kolonial, novel ini mengikuti Saleem melalui kemerdekaan India dan konflik internal, perang dengan Pakistan dan “Keadaan Darurat” yang diumumkan oleh Perdana Menteri Indira Gandhi pada tahun 1970-an. Ini adalah perjalanan dengan awal, tengah dan akhir, tetapi juga perjalanan dengan jalan memutar dan efek khusus yang tak terhitung jumlahnya, dari kekuatan pikiran hingga hidung dengan indera penciuman terdalam.
“Midnight’s Children” adalah kisah dewasa bagi Saleem dan Rushdie. Lahir di India, ia menghabiskan sebagian besar usia dua puluhannya bekerja di London, menulis fiksi yang ia anggap sebagai “sampah yang sangat banyak”. Buku pertamanya, “Grimus,” adalah sebuah novel fantasi yang muncul pada tahun 1975 dan dengan cepat dilupakan (Rushdie sudah lama lebih suka novel itu tetap demikian). Rushdie kemudian berpikir dia mungkin akan mencoba novel tentang masa kecil. Penulisnya lahir delapan minggu setelah kemerdekaan India dan dia segera menyadari kejeniusan dalam membiarkan karakternya muncul pada momen itu sendiri. Dia pertama kali “tersandung” dan mencoba menulis sebagai orang ketiga, ketika dia memutuskan untuk membiarkan Saleem berbicara sendiri.
“Saya terkejut. Itu adalah suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya,” kata Rushdie, yang kini tinggal di New York. “Saya berpikir, ‘Apa itu?’ Itu adalah suara yang sangat malas dan saya memutuskan untuk lari saja. Saya menemukan suaranya dan melalui suaranya saya menemukan suara saya.”
Hingga saat ini, belum ada satu pun buku Rushdie yang dijadikan film dan “Midnight’s Children” tampaknya bukan kandidat yang tepat untuk dijadikan film pertama. Ketika Rushdie pertama kali bertemu dengan sutradara Deepa Mehta, mereka seharusnya mendiskusikan novel terbaru, “Shalimar the Clown.” Namun Mehta, yang filmnya menyertakan nominasi Oscar, “Water”, juga bertanya tentang hak atas “Midnight’s Children”. Rushdie, terkejut dengan ketertarikannya, setuju.
“Itu adalah naluri,” katanya. ‘Jelas dengan berbicara dengannya betapa berartinya buku itu baginya.’
Dia akan membagi hutang atau kredit apa pun. Rushdie menulis skenario (“Deepa memutar lenganku”), memberikan narasi di luar layar dan berkonsultasi erat dengan Mehta dalam produksi, yang dibintangi Satya Bhabba sebagai Saleem. Para penulis biasanya akan menyingkir begitu mereka memberikan hak film, namun Rushdie mencatat sejarah keterlibatan yang mendalam, baik itu John Irving, yang memenangkan Oscar untuk skenario filmnya untuk “The Cider House Rules,” atau Paul Auster, yang sangat menikmati bekerja dengan sutradara Wayne Wang. . pada adaptasi dari ceritanya “Smoke” yang akhirnya mereka sutradarai sekuelnya, “Blue in the Face”.
“Saya tidak berniat mengerjakan ‘Smoke’, tapi sedikit demi sedikit saya tertarik untuk mengerjakannya,” kata Auster. “Itu ternyata menjadi salah satu pengalaman hebat dalam hidup saya.”
“Midnight’s Children” berdurasi 140 menit, lebih lama dari rata-rata film, tapi tidak cukup untuk menangkap semua yang ada di buku Rushdie. Sebaliknya, Rushdie dan Mehta sepakat tentang cara menyingkatnya—penghapusan subplot dan penyimpangan serta perangkat naratif yang digunakan Saleem untuk menceritakan kisahnya kepada seorang wanita bernama Padma.
Salah satu perubahan penting adalah bagian akhir. Dalam film tersebut, kita mendengar Rushdie merefleksikan peristiwa-peristiwa selama beberapa dekade dan menyimpulkan dengan harapan bahwa “semuanya memiliki rasa kebenaran yang otentik, bahwa bagaimanapun juga, itu adalah tindakan cinta.”
Namun novel ini berakhir jauh lebih gelap, seolah mengantisipasi masalah yang akan datang pada Rushdie. Saleem menyatakan bahwa “merupakan hak istimewa dan kutukan bagi anak-anak di tengah malam untuk menjadi tuan sekaligus korban dari zaman mereka, mengabaikan privasi dan tersedot ke dalam pusaran massa yang merusak, tidak dapat hidup atau mati dengan damai.”
“Buku itu dihantui oleh kegelapan masa darurat dan saya tidak ingin mengakhiri film seperti itu,” kata Rushdie saat wawancara. “Saya ingin akhir menjadi semacam permulaan, yang mewakili awal dari hari yang lain.”