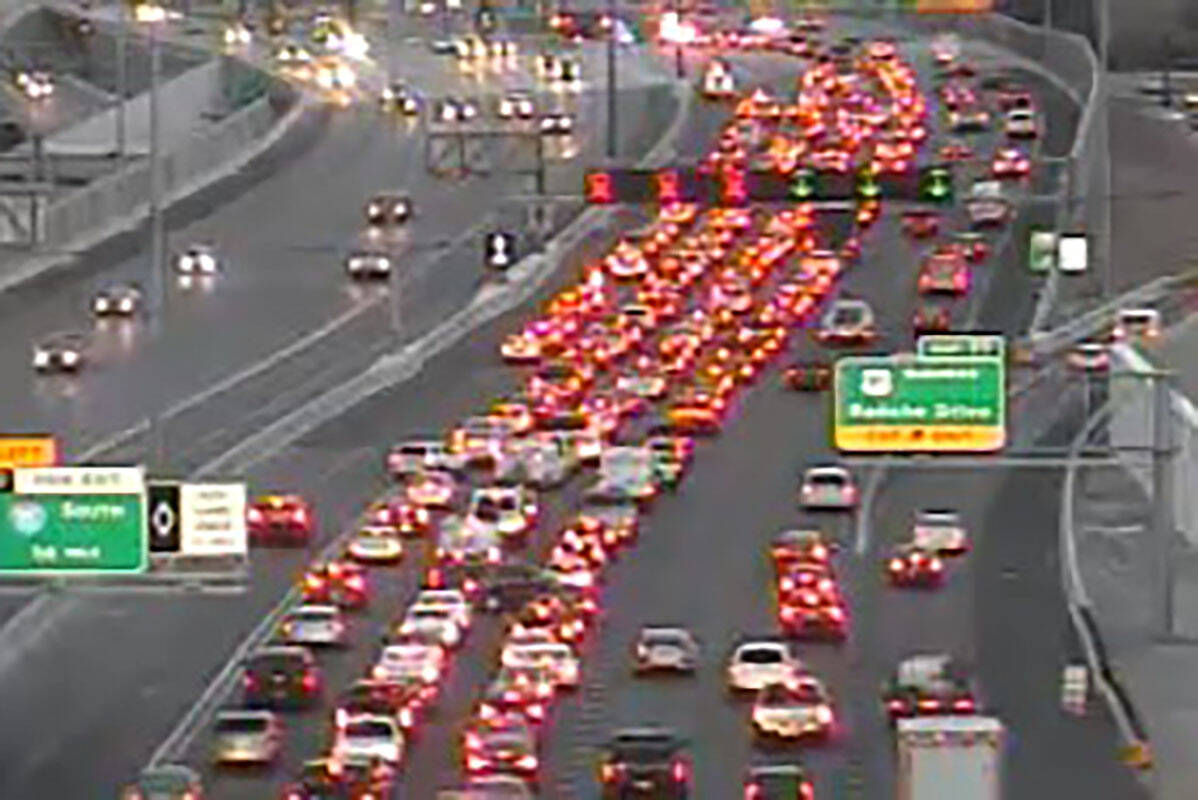OSAKA, Jepang (AP) — Lebih dari 70 tahun yang lalu, pada usia 14 tahun, Kim Bok-dong diperintahkan untuk bekerja oleh penjajah Jepang di Korea. Dia diberitahu bahwa dia akan pergi ke pabrik seragam militer, tetapi berakhir di rumah bordil yang berhubungan dengan militer Jepang di Cina selatan.
Dia harus mengambil rata-rata 15 tentara sehari selama seminggu, dan lusinan pada akhir pekan. Di penghujung hari, dia berdarah dan bahkan tidak bisa berdiri karena sakit. Dia dan gadis-gadis lain diawasi dengan ketat oleh penjaga dan tidak bisa melarikan diri. Itu adalah rahasia yang dia bawa selama beberapa dekade; pria yang kemudian dinikahinya meninggal tanpa pernah diketahui.
Puluhan ribu wanita memiliki cerita serupa untuk diceritakan, atau disembunyikan, tentang pendudukan Jepang di sebagian besar Asia sebelum dan selama Perang Dunia II. Banyak yang tidak lagi hidup, dan mereka yang tersisa masih menunggu Jepang untuk menawarkan kompensasi dan permintaan maaf yang lebih lengkap dari yang telah disampaikan sejauh ini.
“Saya di sini hari ini bukan karena saya ingin, tetapi karena saya harus melakukannya,” kata Kim, sekarang 87 tahun, kepada hadirin yang sebagian besar orang Jepang di sebuah pusat komunitas di Osaka selama akhir pekan. “Saya datang ke sini untuk meminta Jepang memperbaiki pelanggaran masa lalunya. Saya berharap pemerintah Jepang menyelesaikan masalah ini secepat mungkin selagi para wanita lanjut usia kami masih hidup.”
Masalah penggunaan wanita dan gadis Korea, Cina, dan Asia Tenggara oleh Jepang sebagai budak seks – secara halus disebut “wanita penghibur” – tetap mengasingkan Tokyo dari tetangganya hampir 70 tahun setelah berakhirnya perang. Ini adalah luka baru bulan ini ketika salah satu ketua partai nasionalis yang sedang naik daun, Walikota Osaka Toru Hashimoto, mengatakan “wanita penghibur” diperlukan untuk menjaga disiplin militer dan memberikan istirahat kepada pasukan yang lelah berperang.
Komentarnya menuai kemarahan dari Korea Selatan dan China, serta dari Departemen Luar Negeri AS, yang menyebutnya “keterlaluan dan ofensif”.
Hashimoto tidak memberikan bukti tetapi bersikeras bahwa Tokyo dipilih secara tidak adil karena perilaku Perang Dunia II terhadap wanita, dengan mengatakan bahwa beberapa tentara lain memiliki rumah bordil militer pada saat itu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dituduh melakukan perbudakan seksual terorganisir yang tersebar luas yang terkait dengan militer Jepang.
Sejarawan mengatakan hingga 200.000 wanita dari seluruh Asia, termasuk China, Filipina, Indonesia, Thailand, Burma, Hong Kong dan Makau, serta Belanda, dipaksa untuk memberikan seks kepada tentara Jepang.
Bagi banyak orang, bahkan di dalam Jepang, komentar Hashimoto menunjukkan bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, para pemimpin Jepang tidak mau sepenuhnya mengakui ketidakadilan masa perang dan tidak menyentuh sentimen tidak hanya tetangga mereka dan komunitas internasional, tetapi juga banyak dari mereka sendiri. warga.
“Ini bukan masalah masa lalu. Ini adalah masalah berkelanjutan yang melibatkan orang-orang yang masih hidup,” kata Koichi Nakano, seorang profesor ilmu politik di Universitas Sophia. “Jepang dipandang hanya menunggu mereka mati sambil melihat ke arah lain dan menyeret kakinya. Itu terlihat buruk dari sudut pandang kemanusiaan.”
Menurut survei yang dilakukan oleh surat kabar konservatif Sankei dan televisi FNN selama akhir pekan, lebih dari 75 persen orang Jepang mengatakan komentar budak seks Hashimoto tidak pantas, sementara dukungan untuk partainya turun menjadi 6,4 persen – hampir setengah dari bulan lalu.
Komentar tersebut muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang di wilayah tersebut tentang pergeseran nasionalis dalam kepemimpinan politik Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, yang telah menyarankan dia ingin merevisi alasan masa lalu Jepang untuk agresi masa perangnya dan mengubah konstitusi pasifisnya.
Pada tahun 1993, Jepang secara resmi meminta maaf atas “wanita penghibur” dalam pernyataan penting oleh Sekretaris Kabinet saat itu Yohei Kono, yang mengakui “rasa sakit yang tak terukur dan luka fisik dan psikologis yang tak tersembuhkan.”
Namun Kim dan perempuan lainnya menginginkan permintaan maaf penuh yang disetujui oleh parlemen dan kompensasi resmi dari pemerintah. Tokyo menentang ini, mengatakan pampasan perang dengan Korea Selatan tercakup dalam perjanjian yang memulihkan hubungan pascaperang. Pada tahun 1995, Tokyo menciptakan dana yang menggunakan sumbangan pribadi sebagai cara bagi Jepang untuk membayar mantan budak seks tanpa memberikan kompensasi resmi.
Dana tersebut memberikan masing-masing 2 juta yen ($20.000) kepada sekitar 280 wanita di Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan, dan mendanai panti jompo bagi para korban Indonesia dan bantuan medis kepada sekitar 80 mantan budak seks Belanda.
Di Korea Selatan, 207 wanita secara resmi maju dan diakui sebagai penerima yang memenuhi syarat. Tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar menerima uang itu karena kritik terhadap dana swasta. Sebaliknya, mereka menerima dukungan dari pemerintah Korea Selatan dan kelompok pendukung.
Di Jepang, sentimen publik menjadi kurang berbelas kasih terhadap korban Asia dari agresi masa perang negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Referensi untuk “wanita penghibur” pernah ada di buku teks sejarah sekolah telah hilang.
Sebagian besar perdebatan tentang “wanita penghibur” masih berfokus pada peran apa yang dimainkan pemerintah dalam mengatur rumah bordil pada saat itu, dan apakah – atau sampai sejauh mana – para wanita tersebut dipaksa. Pernyataan Kono mengatakan militer secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pendirian dan pengelolaan rumah bordil garis depan dan pemindahan perempuan, dan bahwa banyak perempuan dalam banyak kasus “direkrut di luar keinginan mereka dengan cara memikat dan memaksa.”
Nobuo Ishihara, yang saat itu menjadi wakil sekretaris kabinet, mengatakan pada Maret 2006 bahwa wawancara dengan 16 wanita Korea Selatan di Seoul menyimpulkan adanya pemaksaan, meskipun tidak ada dokumen resmi yang menunjukkannya.
“Setelah mewawancarai 16 wanita penghibur, kami mulai percaya bahwa apa yang mereka katakan tidak dapat direkayasa. Kami pikir tidak diragukan lagi bahwa mereka dipaksa menjadi wanita penghibur yang bertentangan dengan keinginan mereka,” kata Ishihara. “Berdasarkan laporan tim investigasi, kami sebagai pemerintah berkesimpulan adanya pemaksaan.”
Investigasi pemerintah juga menemukan bahwa banyak korban Belanda dipilih dari kamp konsentrasi dan dikirim secara paksa ke rumah bordil, sementara korban di Filipina dan Indonesia diperkosa, diculik dan dipaksa untuk memberikan tahanan seks di medan pertempuran.
Hashimoto, 43, mencoba menenangkan keributan pada hari Senin, mengatakan pada konferensi pers yang padat bahwa dia secara pribadi tidak menyetujui penggunaan “wanita penghibur”, yang dia sebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Namun dia berulang kali menegaskan bahwa pemerintah masa perang Jepang tidak secara sistematis memaksa gadis dan wanita untuk menjadi pelacur, meskipun dia mengakui bahwa beberapa mungkin telah ditipu dan dipaksa. Ia mengatakan, catatan sejarahnya tidak jelas, yang senada dengan pandangan Abe bahwa tidak ada bukti bahwa para perempuan itu dipaksa karena perintah negara. Dia mengatakan sejarawan dari Jepang dan Korea Selatan harus menyelesaikan masalah ini.
Hashimoto mengakui bahwa kekeruhan ini mungkin merupakan kendala terpenting dalam hubungan Jepang dengan Korea Selatan.
Sejarawan Universitas Chuo, Yoshiaki Yoshimi, salah satu pakar “wanita penghibur” Jepang yang paling dihormati, mengkritik pemerintah Jepang karena menerima interpretasi yang sangat sempit tentang apa yang dimaksud dengan pemaksaan.
Dia mengatakan dokumen menunjukkan bahwa “wanita penghibur” yang direkrut di Jepang kebanyakan adalah profesional dewasa, meskipun banyak yang dijual ke industri seks oleh keluarga miskin mereka. Namun, di negara-negara Asia yang diinvasi oleh Jepang, tidak ada pertimbangan tentang hak anak di bawah umur atau hak untuk berhenti, yang menurutnya merupakan paksaan menurut standar internasional.
“Baik Perdana Menteri Abe maupun Walikota Hashimoto tidak mencoba melihat bagaimana gadis dan wanita muda itu dilecehkan. Pandangan mereka berbeda dengan pandangan internasional,” katanya.
Kim diseret melalui Asia, dari Hong Kong ke Singapura dan Indonesia, hingga perang berakhir pada tahun 1945. Dia dibebaskan di Singapura dan kembali ke rumah pada tahun 1946. Dia kemudian menikah, tetapi – seperti kebanyakan mantan budak seks – tidak pernah bisa mengungkapkan masa lalunya kepada siapa pun kecuali ibunya – sampai beberapa dekade kemudian.
“Bahkan ketika saya kembali ke tanah air saya, itu tidak pernah menjadi pembebasan sejati bagi saya,” katanya kepada para pendengar di pusat komunitas. “Bagaimana saya bisa memberi tahu siapa pun apa yang terjadi pada saya selama perang? Itu hidup dengan benjolan besar di dadaku.”
Dia akhirnya memecah kebisuannya beberapa tahun setelah suaminya meninggal pada tahun 1981. Kemudian, dia bergabung dengan sekelompok wanita yang mencari pengakuan resmi sebagai korban perbudakan seks Jepang.
Kim telah berkeliling dunia untuk menceritakan kisahnya dan berpartisipasi dalam protes mingguan di depan kedutaan Jepang di Seoul.
Kim dan mantan budak seks lainnya, Kil Won-ok yang berusia 84 tahun, telah mencari pertemuan dengan Hashimoto selama beberapa waktu ketika dia menyampaikan komentarnya bulan ini. Dia kemudian menawarkan untuk bertemu dengan mereka, tetapi mereka membatalkan, mengatakan bahwa mereka tidak menyadari dia menyesal dan tidak ingin digunakan olehnya untuk merehabilitasi citranya. Sebaliknya, mereka berbicara kepada publik di Osaka.
“Kita tidak akan lama lagi di sana,” kata Kil. “Tapi kami harus menceritakan kisah kami kepada Anda karena kami tidak ingin kesalahan yang sama terulang.”