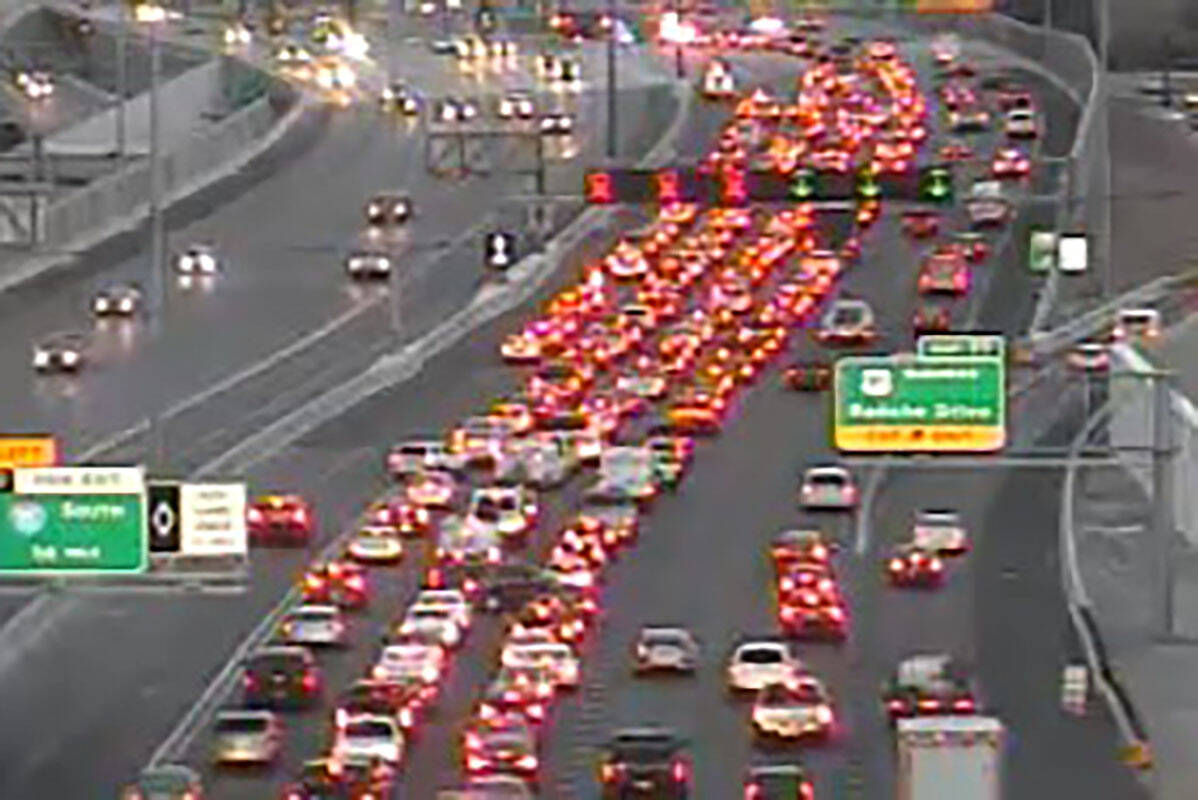BIRMINGHAM, Alabama (AP) – Sudah setengah abad sejak Pendeta Martin Luther King Jr. menyatakan mimpi yang akan bergema sepanjang sejarah.
“Saya bermimpi bahwa suatu hari di Alabama… anak laki-laki dan perempuan kulit hitam akan dapat bergandengan tangan dengan anak laki-laki kulit putih dan perempuan kulit putih sebagai saudara dan saudari,” kata pemimpin hak-hak sipil itu pada tanggal 28 Agustus 1963. .
Ketika Amerika Serikat memperingati 50 tahun pidato King yang bertajuk “I Have A Dream”, mungkin tidak ada tempat yang lebih baik untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai setelah seruan bersejarahnya selain di Birmingham, Alabama.
Kota ini, yang pernah menjadi simbol tempat duduk bus dan air mancur yang terpisah, merupakan tempat suci dalam sejarah hak-hak sipil. Di sinilah anak-anak yang melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan persamaan hak dipenjara, di mana para pengunjuk rasa diserang oleh anjing polisi yang menggeram dan dipukuli dengan selang pemadam kebakaran bertekanan tinggi. Di sinilah empat gadis kecil yang mengenakan pakaian terbaik di hari Minggu terbunuh ketika dinamit yang ditanam oleh anggota Ku Klux Klan merobek gereja mereka.
Ini adalah Birmingham di masa lalu. Kota yang dikutuk Raja karena “catatan kebrutalan yang buruk”. Kota tempat dia menulis “Surat dari Penjara Birmingham” yang penuh semangat, menyatakan “tanggung jawab moral untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil”. Kota tempat gerakan ini berkumpul, menemukan suaranya dan menjadi landasan bagi undang-undang hak-hak sipil yang penting.
Jadi, apakah impian King mengenai kesetaraan telah terwujud di sini dan apakah Birmingham telah berhasil melampaui masa lalunya yang penuh masalah?
Dalam banyak hal, jawabannya adalah ya, kota ini telah berubah dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Nama bandara ini diambil dari nama tokoh pembela hak-hak sipil yang tak kenal takut, mendiang Pendeta Fred Shuttlesworth. Walikota berkulit hitam telah menduduki Balai Kota sejak tahun 1979, sebagian karena banyak penduduk kulit putih bermigrasi ke pinggiran kota, sebuah pola yang lazim di perkotaan Amerika. Saat ini, hampir 75 persen penduduknya berkulit hitam.
Kota ini secara langsung memperingati peristiwa memalukan tahun 1960-an. Di antara bunga-bunga di Kelly Ingram Park, terdapat pengingat yang jelas akan tabrakan yang buruk itu. Ada satu patung seorang pengunjuk rasa muda, tangannya terentang, sementara seorang polisi memegangnya dengan satu tangan dan memegang seekor anjing gembala Jerman di tangan lainnya. Ada juga patung memperingati Raja.
Meskipun rasisme terang-terangan pada tahun 1960-an sudah lama hilang, isunya belum hilang.
Hambatan hukum dan sosial yang melarang orang kulit hitam bersekolah dan bekerja sudah lama terjadi, namun kesenjangan ekonomi masih terjadi. Hitam dan putih bekerja sama dan makan berdampingan di restoran, tetapi biasanya tidak bercampur setelah jam 5 sore
Glennon Threatt berusia 7 tahun di Birmingham ketika King mengumumkan visinya tentang masyarakat buta warna selama Pawai di Washington.
Tidak lama kemudian, Threatt termasuk di antara tiga siswa kulit hitam berbakat yang terdaftar di sekolah dasar kulit putih. Dia diludahi, dipukuli, dan disebut sebagai penghinaan rasial.
Saat masih muda, dia menaiki bus menuju Universitas Princeton dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke Birmingham.
Dia akan berubah pikiran. Setelah pensiun pada tahun 1997, Threatt bergabung dengan firma hukum yang sudah mapan — sesuatu yang tidak terpikirkan 50 tahun sebelumnya. Baik dia maupun kotanya telah berubah, katanya.
Threatt, kini berusia 57 tahun, kadang-kadang bertemu dengan teman sekolah lamanya – seorang wakil presiden bank – yang merupakan salah satu penyiksanya. Mereka selalu mengobrol menyenangkan. Tapi dia tidak pernah lupa.
“Aku menyukainya,” katanya. “Saya tidak berpikir dia rasis. Dia adalah seorang anak yang terjebak dalam situasi sosial seperti saya. …. Anda harus mengatasinya untuk bertahan hidup di Selatan. … Jika tidak, Anda hanya akan berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri dan kebencian dan Anda tidak bergerak maju.”
Threatt sebagian terinspirasi untuk menjadi pengacara oleh Arthur Shores, seorang perintis pengacara hak-hak sipil yang berjuang untuk desegregasi Universitas Alabama. Rumah Shores dibom dua kali pada tahun 1963, selang waktu dua minggu.
Putri Shores, Helen, tumbuh menentang segregasi dan pernah minum dari air mancur “putih”—sebuah tindakan pembangkangan yang berujung pada pencambukan ketika dia sampai di rumah. Pada usia 12, dia mengarahkan Colt .45 ke sepasang pria kulit putih yang melewati rumah keluarganya dan melontarkan kata-kata kotor rasial. Ayahnya, katanya, memukul lengannya, pelurunya melesat ke udara dan dia dengan cepat mengambil pistolnya.
Shores Lee juga meninggalkan Birmingham, membuat janji yang sama untuk tidak kembali. Dia pun akhirnya berubah pikiran dan akhirnya menjadi hakim di kota tersebut.
Pada tahun-tahun awalnya sebagai hakim, kenangnya, beberapa pengacara secara tegas menolak untuk berdiri sebagaimana lazimnya ketika hakim memasuki ruang sidang. Dan, katanya, dia kadang-kadang melihat pengacara yang tidak menghormati klien minoritasnya.
“Rasisme masih hidup dan sejahtera di Selatan,” kata Shores Lee. “Tindakan laki-laki di sini bisa dilegalkan, tapi pikiran dan hati mereka tidak bisa dilegalkan dalam kaitannya dengan cara berpikir dan perasaan mereka terhadap orang kulit hitam dan Hispanik.”
James Rotch, seorang pengacara kulit putih, meluncurkan Birmingham Pledge pada tahun 1998 untuk menghilangkan rasisme dan prasangka.
“Ikrar” tersebut telah berkembang menjadi sebuah yayasan dengan konferensi, materi pendidikan yang digunakan di seluruh AS dan acara minggu khusus yang diadakan sekitar peringatan bulan September pemboman Gereja Baptis Sixteenth Street yang menewaskan empat gadis tersebut.
Dalam 15 tahun terakhir, Rotch mengatakan kedua balapan menjadi lebih nyaman satu sama lain. Dan bagi mereka yang berusia 30 tahun ke bawah, “mereka benar-benar tidak mengerti mengapa ada orang yang berprasangka buruk,” katanya. “Mereka mudah berbaur dan mereka tidak melihat apa masalah besarnya.”
Namun ada batasan dalam sosialisasi.
Impian King adalah “nyata di siang hari” di tempat kerja dan restoran, kata Jim Reed, pemilik toko buku kulit putih. “Ketika orang tidak memikirkannya, hal itu menjadi kenyataan,” katanya. Namun begitu sampai di rumah, mereka cenderung tidak memperluas lingkarannya.
“Masyarakat tidak tahu bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut,” meskipun ada yang ingin melakukannya, katanya. “Saya melihat butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Generasi harus berubah.”
Di Gereja Iman Lebih Dari Penakluk, Pendeta Steve Green berkhotbah kepada jemaat yang tidak mungkin ada pada Hari Raja.
Ada lulusan dari universitas yang dulunya terpisah. Generasi anak-anak yang merasa nyaman dengan hubungan campuran ras. Dan orang-orang yang berupaya mendapatkan suara untuk Barack Obama, presiden kulit hitam pertama Amerika.
Namun ada satu hal yang tetap: jemaat Green sekitar 90 persen berkulit hitam, mengingatkan pernyataan King yang sering dikutip bahwa hari Minggu pukul 11.00 adalah “jam paling segregasi di Amerika yang beragama Kristen”.
King, kata pendeta tersebut, akan mengacu pada Alkitab untuk menjelaskan bahwa 50 tahun bukanlah waktu yang lama untuk mengubah seluruh masyarakat.
“Sebagai seorang pengkhotbah, saya pikir dia akan menggunakan prinsip kitab suci tentang waktu menabur dan menuai sebagai dasarnya. Saya rasa sudah banyak benih yang ditanam,” ujarnya. “Mereka diasuh sedikit demi sedikit. Tapi menurutku ini belum waktunya panen.”
___
Penulis Nasional Associated Press Sharon Cohen berkontribusi pada cerita ini. Dia dapat dihubungi di [email protected]