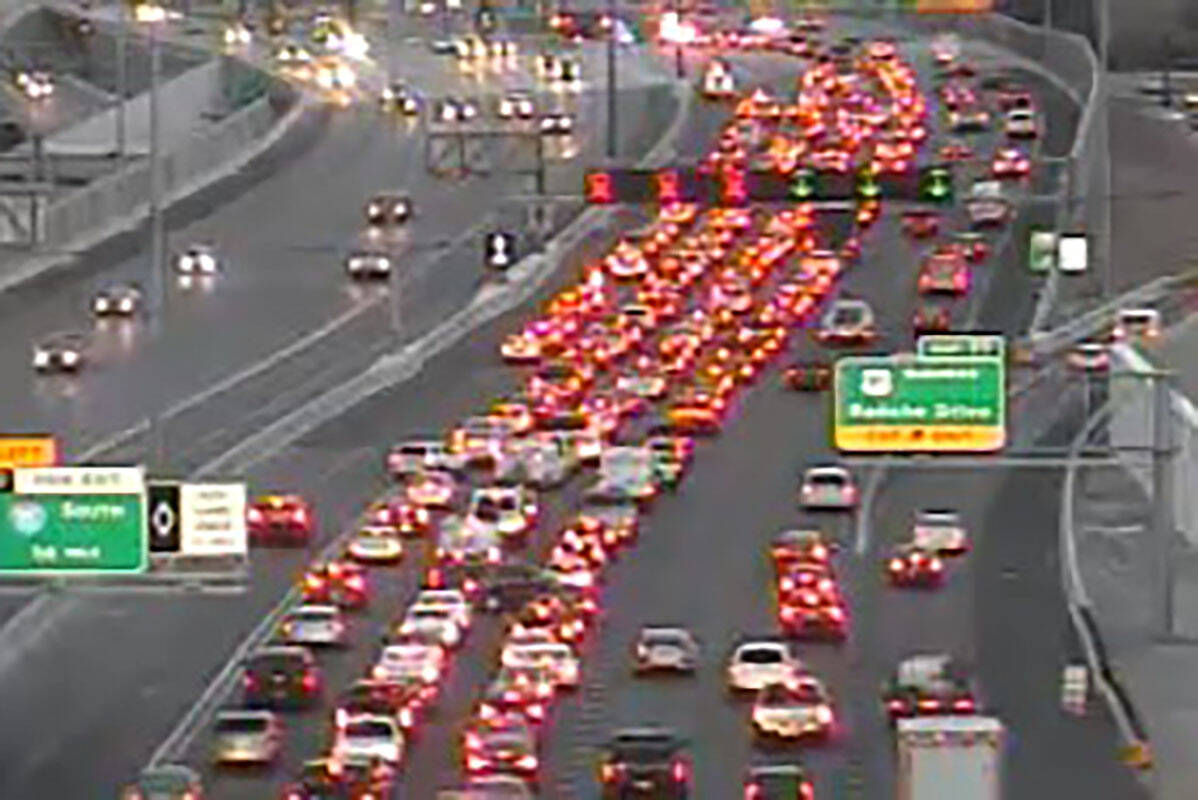YANGON, Myanmar (AP) – Dua puluh lima tahun kemudian, Anda masih dapat melihat ketakutan di mata para dokter – dua pemuda menggendong seorang siswi, bajunya berlumuran darah, melalui jalan-jalan di mana tentara berbaris dalam protes pro-demokrasi dihancurkan secara brutal.
Foto tersebut, yang menonjol ketika muncul di sampul Newsweek, melambangkan kekalahan pemberontakan tahun 1988 di negara yang saat itu bernama Burma. Berakhirnya pemberontakan memperkuat kekuatan militer, memenjarakan ribuan aktivis dan membantu meluncurkan calon penerima Nobel, Aung San Suu Kyi.
Baru sekarang, satu generasi setelah peristiwa hari itu yang dikenal sebagai “8.8.88”, Win Zaw mulai membicarakan semuanya.
Dia adalah dokter di belakang layar, kacamatanya turun ke hidung saat dia berjuang untuk menggendong gadis yang berlumuran darah itu. Saat ini, dua tahun setelah junta militer Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-sipil, ia masih ragu untuk membatalkan keputusan tersebut. Dan bagi banyak orang di Myanmar, sejarah menyakitkan yang mereka alami hanya sekedar bisikan.
“Pintunya sedikit terbuka,” kata Win, kini berusia 48 tahun, mengambil jeda panjang saat mencoba menemukan kata-kata yang tepat. “Saya ingin berbicara, demi sejarah, dan semua orang yang meninggal. Dalam hatiku aku merasa inilah saat yang tepat. Tapi tetap saja aku merasa tidak aman.”
Ini adalah kisah dari begitu banyak negara yang berjuang menghadapi akibat dari kekejaman mereka sendiri. Kapan saat yang tepat untuk membuka pembicaraan yang sudah lama tersembunyi, untuk menghadapi masa lalu, untuk mengatasinya?
Argentina menghadapi hal ini pada tahun-tahun setelah Perang Kotor pada tahun 1970an, ketika negara tersebut mencoba untuk mengatasi penindasan militer selama beberapa dekade. Hal ini terjadi di Kamboja, dimana kebrutalan rezim Pol Pot melatih seluruh bangsa untuk tetap diam.
Hal ini telah terjadi berulang kali di Tiongkok modern, di mana tindakan keras terhadap Tiananmen pada tahun 1989 masih menjadi topik yang tabu, dan bahkan realitas sejarah yang sudah berusia setengah abad mengenai “Lompatan Jauh ke Depan”—kebijakan Mao Zedong yang membawa bencana yang menyebabkan meluasnya kelaparan dan kematian. puluhan juta orang pada akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an – baru terungkap akhir-akhir ini.
“Kami bahkan menghindari merujuknya,” kata Dali Yang, seorang ilmuwan politik di Universitas Chicago yang lahir dan besar di Tiongkok. “Masih ada tarik-menarik antara sensor dan orang-orang yang ingin mengatakan kebenaran… Namun secara halus, secara bertahap, hal ini mulai berubah.”
Namun, ketika perubahan terjadi, dari mana datangnya? Bagaimana rasa takut dan diam bisa hilang sehingga suatu negara bisa mendiskusikan sejarahnya secara terbuka?
Beberapa di antaranya hanyalah kekuatan waktu. Politisi yang berkuasa akan mati. Peristiwa traumatis dalam sejarah dikalahkan oleh trauma yang lebih baru. Langkah-langkah kecil menuju kebenaran bertambah. Akhirnya, detail mulai terungkap.
Kebenaran tentang kelaparan, misalnya, telah lama diketahui secara kasar di luar Tiongkok, namun hanya diketahui di dalam negeri oleh elit politik dan segelintir cendekiawan. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan pemerintah mulai mengakui bahwa kebijakan Mao juga patut disalahkan.
Myanmar, seperti Tiongkok, adalah negara yang pemerintahan diktatornya sudah tidak terlalu parah, meski masih jauh dari kata demokratis. Dan sejarah Myanmar telah melahirkan generasi-generasi yang pesimis.
Setelah gen. Ne Win mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962, yang mengubah negara ini dari salah satu negara terkaya di Asia menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kebencian terhadap kebijakan Ne Win yang korup dan tidak efektif mulai meningkat pada tahun 1987 dan berlanjut hingga tanggal 8 Agustus 1988, ketika pemogokan nasional menyebabkan protes yang meluas dan penindasan militer yang cepat. Seorang presiden sipil, yang ditunjuk di tengah pertumpahan darah, berkuasa kurang dari sebulan sebelum digulingkan dalam kudeta 18 September.
Tidak ada pejabat pemerintah yang pernah dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan yang menyebabkan sekitar 3.000 orang tewas.
Pada hari Kamis, ribuan orang berkumpul untuk berpidato, pameran dan pawai mengenang pemberontakan tahun 1988. Di Yangon, sekitar 150 pengunjuk rasa damai menerobos polisi dan pihak berwenang setempat yang meminta mereka berhenti. Beberapa tahun yang lalu, konfrontasi seperti ini hampir pasti berakhir dengan kekerasan. Namun pada hari Kamis, para pengunjuk rasa terus berjalan.
“Saya baru berusia 11 tahun ketika peristiwa ’88 terjadi, dan saya tidak ingat banyak kecuali orang-orang mengatakan ‘Urusan kita!’ teriaknya,” kata Aung Thaw, seorang penjual komputer berusia 36 tahun. Dia mengatakan dia bergabung dalam protes tersebut karena “Saya ingin memberi hormat kepada mereka yang berani berpartisipasi dalam gerakan bersejarah ini.”
Selama protes setelah kudeta September, Win Zaw, yang saat itu adalah seorang dokter di rumah sakit utama Yangon, mendengar bahwa para pengunjuk rasa telah ditembak oleh tentara dan memerlukan perhatian medis.
Bekerja dengan rekannya yang lebih tua, Saw Lwin, dia berulang kali melakukan perjalanan dengan ambulans ke zona protes dan membawa korban luka ke rumah sakit.
Pada perjalanan ketiga, ketika mereka berbelok ke Merchant Road, salah satu jalan utama kota, mereka melihat puluhan pengunjuk rasa tewas dan terluka. Darah ada dimana-mana.
Kedua dokter itu memperhatikan seorang gadis muda, terluka parah. Banyak dari pengunjuk rasa paling sengit adalah pelajar, dan gadis tersebut mengenakan seragam siswa sekolah menengah: longyi berwarna gelap dan blus putih. Kemeja itu hampir seluruhnya merah karena darah.
“Saya mendengarkan baik-baik dan ternyata jantungnya masih berdetak,” kata Win. “Dia berbisik, ‘Saudaraku, tolong aku.'”
Kedua dokter tersebut mendesaknya untuk tidak menyerah dan berlari ke ambulans bersama Win Maw Oo yang berusia 16 tahun. Di situlah Steve Lehman, seorang fotografer Amerika berusia 24 tahun, memotret mereka, ketakutan dan kelelahan mereka terlihat jelas, jas dokter mereka berkibar.
Gadis itu tidak akan pernah melihat gambar itu. Dia meninggal pada malam yang sama.
Beberapa minggu kemudian, ketika foto itu muncul di sampul Newsweek, Win Zaw khawatir akan ada masalah. Pada tahun 1992, dia ditahan oleh tentara, ditutup matanya, dibawa ke pusat interogasi dan ditahan selama lima hari. Meskipun dia tidak disiksa, dia sangat terguncang dengan penangkapan tersebut. Ia juga masuk daftar hitam pemerintah, dan tidak bisa mendapatkan paspor selama hampir 20 tahun. Dia akhirnya menjalankan klinik swasta.
Keadaan menjadi lebih buruk bagi Saw Lwin. Ayahnya, seorang manajer puncak sebuah lembaga penyiaran negara, terpaksa pensiun. Saw yang merasa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa ayahnya menjadi depresi. Pada tahun 1996 dia bunuh diri.
“Saya kehilangan seorang kawan, seorang teman,” kata Win Zaw.
Dua puluh lima tahun setelah tindakan keras tersebut, masih banyak hal yang belum terucapkan di Myanmar. Ribuan orang menghilang ke penjara-penjara di negara tersebut pada masa pemerintahan militer, beberapa di antaranya selama bertahun-tahun dan sering kali hanya karena menyebarkan pamflet. Para penyiksa di pusat interogasi tetap bebas, begitu pula penjaga penjara dan orang-orang yang memberi perintah.
“Jika pemerintah mengakui kekejaman di masa lalu dan berkomitmen terhadap akuntabilitas, peringatan 8.8.88 bisa menjadi momen penting untuk mengatasi pemerintahan yang menindas selama beberapa dekade,” kata Brad Adams, direktur Asia untuk Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan. “Ini bahkan bisa menjadi awal dari sebuah era baru jika militer dan pemerintah beralih dari penolakan ke pengakuan dan dari impunitas ke keadilan.”
Namun ketika para aktivis menyerukan penyelidikan, atau bahkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti Afrika Selatan, para jenderal yang berkuasa dan pemerintah sangat ingin melupakan sejarah, menyambut berakhirnya sanksi dan menyaksikan bagaimana perekonomian berkembang. Wisatawan kini berbondong-bondong ke Myanmar. Perjanjian perdagangan ditandatangani. Dan Win Zaw sedang menulis buku.
Meskipun ia merasa gugup untuk mengumumkannya kepada publik, ia mengatakan apa yang terjadi selama protes tersebut harus diingat: “8.8.88 tidak boleh dilupakan. Kami harus menjaga semangat tetap hidup.”
___
Sullivan melaporkan dari New Delhi.